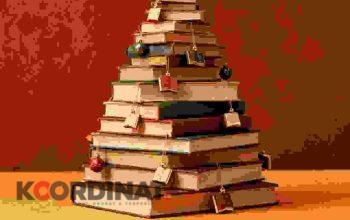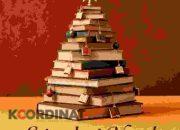Oleh : Muhsin Labib
*Awal abad ke-20 menjadi titik kelam bagi sebagian besar umat Islam. Kesultanan Utsmaniyah, yang selama berabad-abad menjadi mercusuar persatuan politik dan spiritual, akhirnya runtuh. Imperium yang membentang dari Balkan hingga Afrika Utara ini rapuh akibat korupsi yang merajalela, sentralisasi kebijakan yang represif dan memicu pembangkangan, serta tekanan dari Eropa dan gelombang nasionalisme.
Sejarah juga mencatat salah satu noda tergelap Dinasti Utsmaniyah: genosida brutal terhadap populasi Kristen Armenia, yang dikenal sebagai pembantaian Hamidian pada 1894-1896. Peristiwa tragis ini, yang berlangsung terutama selama Perang Dunia I, mengakibatkan kematian lebih dari satu juta jiwa. Orang-orang Armenia dipaksa melakukan “mars kematian” ke gurun Suriah tanpa makanan dan air, menjadi sasaran kelaparan, penyakit, dan serangan brutal militer serta kelompok paramiliter Utsmaniyah. Warisan peradaban Armenia di Anatolia Timur yang telah berumur ribuan tahun pun musnah. Peristiwa ini secara luas diakui sebagai genosida pertama di abad ke-20, sebuah kejahatan kemanusiaan yang hingga kini masih menjadi luka terbuka dan sengketa historis mendalam antara Armenia dan Turki.
Perang Dunia I (1914-1918) mempercepat kehancuran Utsmaniyah. Kekalahan dalam perang membuat wilayahnya dicabik-cabik melalui Perjanjian Sevres (1920). Meskipun Mustafa Kemal Atatürk memenangkan Perang Kemerdekaan Turki, ia tidak dapat menyelamatkan kesultanan. Pada 1 November 1922, kesultanan dihapus, dan pada 3 Maret 1924, pukulan terberat mendarat: kekhalifahan lenyap, merobek simbol persatuan umat Islam.
Runtuhnya kekhalifahan dirasakan sebagai akhir zaman keemasan, menyulut duka dan kegelisahan global. Dari puing-puing kekecewaan ini, muncul gerakan revivalis Islam, termasuk gagasan untuk menghidupkan kembali khilafah demi mengembalikan kejayaan yang hilang.
Kelahiran Hizbut Tahrir dan Visi Khilafah Global
Di tengah keputusasaan, Hizbut Tahrir (HT) lahir di Yerusalem pada 1953, dipimpin Taqiyuddin an-Nabhani, seorang ulama visioner yang mendambakan kebangkitan Islam melalui kekhalifahan global. Menolak sistem negara-bangsa, HT menyerukan perubahan melalui dakwah intelektual tanpa kekerasan, menyasar intelektual, mahasiswa, dan profesional yang haus solusi atas kegelisahan zaman. Gerakan ini menyebar cepat ke dunia Arab, Asia Tenggara, dan akhirnya Indonesia, membawa visi khilafah sebagai obat keterpurukan umat.
Semangat HT juga terpicu oleh Revolusi Islam Iran 1979, yang menunjukkan bagaimana agama bisa menjadi kekuatan politik dominan. Keberhasilan Syiah mendirikan republik Islam di bawah ulama memicu refleksi di kalangan Sunni: mengapa mayoritas Sunni terpecah, sedangkan Syiah mampu bersatu? Kecemburuan ini, bercampur kerinduan akan kejayaan pasca-Utsmaniyah, mengobarkan ambisi mereka untuk mewujudkan khilafah.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengakar pada akhir 1980-an melalui gerakan Tarbiyah, fenomena dakwah mahasiswa yang menekankan pembinaan keislaman lewat kelompok-kelompok kecil (liqa’). Ide khilafah HTI resonan dengan sebagian aktivis Tarbiyah, namun tidak semua berlabuh di HTI. Banyak yang memilih jalur politik praktis, mendirikan Partai Keadilan (1998), yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2003. Awalnya, batas antara Tarbiyah, HTI, dan PK/PKS samar, bersatu dalam semangat Islam sebagai solusi. Namun, perbedaan strategi memicu perpecahan: HTI menolak demokrasi, fokus pada khilafah sebagai tujuan tunggal, sementara PKS merangkul Pancasila dan berjuang dalam sistem demokrasi. “Perceraian” ini tak terelakkan, dan HTI akhirnya dibubarkan pemerintah pada 2017 karena dianggap mengancam ideologi negara.
Isu khilafah diwarnai ambiguitas teologis. Mainstream umat mengimani khilafah dan menghormati para sahabat Nabi sebagai penghubung dan distributor ajaran Nabi, terutama sepuluh yang ditetapkan sebagai pemegang garansi surga. Bahkan figur kontroversial Muawiyah pun tetap dihormati karena para sahabat memperoleh privilege perlakuan yurisprudensial khusus tanpa boleh dipertanyakan dan digugat jejak sepak terjang mereka senegatif apapun. Namun, proses suksesi khalifah pertama—Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali—berbeda, bahkan kadang bertentangan. Ketidakseragaman ini menciptakan dilema: apakah khilafah bisa dijadikan pilar doktrin setara rukun iman?
Fakta berbicara: khilafah tidak termasuk dalam enam rukun iman (Allah, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, qada dan qadar). Absennya khilafah dari fondasi akidah menimbulkan pertanyaan: apakah khilafah benar-benar imperatif teologis? Jika tidak, perjuangan menegakkannya—seperti yang digaungkan HTI—kehilangan pijakan kokoh. Ketiadaan khilafah dalam rukun iman membuka ruang ijtihad, memungkinkan umat mencari model kepemimpinan yang relevan dengan zaman, tanpa terikat pada idealisasi historis.
Penolakan terhadap HTI tidak hanya dari negara, tetapi juga kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. Meskipun mengakui khilafah secara teologis, mereka menilai visi HTI tak relevan di Indonesia yang majemuk. Pancasila dan negara-bangsa dipandang sebagai ijtihad politik final, mengutamakan persatuan dan stabilitas.