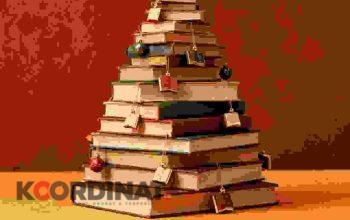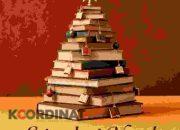Oleh : Jhojo Rumampuk.
Koordinat.co, Opini. Jika lembaga legislatif adalah benteng terakhir check and balance demokrasi, maka apa yang terjadi di DPRD Provinsi Gorontalo hari ini memberikan sinyal keras bahwa benteng itu sedang retak, bukan oleh serangan dari luar, tetapi oleh kelalaian, arogansi, dan inkonsistensi dari aktor-aktor yang justru duduk di dalamnya.
Di tengah polemik panjang sektor pertambangan,mulai dari kegiatan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin), konflik kepentingan korporasi, hingga tuntutan masyarakat penambang lokal. Langkah Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, yang melakukan sidak ke lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango sendirian, bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan hukum, etika, dan politik, Apakah itu tugas pengawasan atau aksi teatrikal berkepentingan?
Peraturan terbaru yang disahkan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo telah mengatur mekanisme kerja komisi dan pansus secara tegas bahwa setiap bentuk pengawasan lapangan, termasuk sidak, harus dilandasi rapat internal dan disetujui minimal setengah dari jumlah anggota yang tergabung dalam komisi atau pansus.
Namun kenyataannya, Ketua Komisi II malah bertindak seolah-olah kewenangan legislatif adalah hak pribadi. Ia turun ke lapangan tanpa mandat, tanpa rapat, tanpa kehadiran anggota lain, dan tanpa persetujuan komisi. Maka wajar jika tindakan tersebut patut disebut bukan sebagai pengawasan resmi, tetapi aksi ilegal dalam konteks tata kelola parlemen.
Karena apa artinya tata tertib jika orang pertama yang melanggarnya adalah pejabat yang seharusnya menegakkan?
Lebih ironis lagi, masa kerja Pansus Pertambangan telah berakhir. Namun, alih-alih menunjukkan kedewasaan administratif bahwa tugasnya telah selesai, tindakan-tindakan personal justru menimbulkan kesan bahwa masih ada kepentingan yang ingin dimainkan di luar landasan kelembagaan.
Apalagi publik masih menyimpan ingatan tentang rekomendasi pansus yang dinilai berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak perusahaan dibanding masyarakat penambang lokal. Ketika pansus diminta revisi karena keberpihakan yang dipertanyakan, lalu muncul sidak sepihak oleh aktor yang terlibat di dalamnya, sulit rasanya menghindari pertanyaan,
Apakah ini pengawasan? Atau proses negoisasi kepentingan yang belum selesai?
Pengawasan legislatif bukan tugas personal, melainkan tindakan kolektif-kolegial. Di sinilah letak persoalan moralnya: Ketua Komisi II tidak hanya melangkahi prosedur, tetapi juga merusak kepercayaan politik internal.
Informasi yang berkembang menunjukkan adanya gelombang keberatan dari sejumlah anggota Komisi II yang merasa nama komisi dicatut untuk agenda pribadi yang tidak pernah dirapatkan. Dan hal terebut bukan lagi hanya pelanggaran administrasi, Tapi ini pembusukan etika politik.
Karena ketika komisi yang harusnya bekerja secara legal formal berubah menjadi kendaraan personalisasi kekuasaan, maka mekanisme demokrasi telah dirusak dari dalam. Ketika pola kerja seperti ini dibiarkan, akibatnya bukan hanya merusak reputasi satu orang, tetapi juga mengacaukan mekanisme checks and balances, melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan, menghilangkan legitimasi rekomendasi pansus sebelumnya, serta membuka preseden bahwa aturan internal tidak harus dipatuhi.
Ketika seorang pejabat publik melakukan tindakan yang menyimpang dari prosedur, kemudian mengaku sebagai korban ketika menerima kritik atau respon hukum, maka fenomena ini masuk dalam pola victim playing atau flym victim:
Pelaku menciptakan konflik atau masalah, lalu membungkus dirinya sebagai pihak yang dizalimi untuk menggeser persepsi publik.
Institusi DPRD adalah pusat legitimasi politik rakyat. Jika ada anggota yang menggunakan nama lembaga untuk kepentingan personal, maka yang tercoreng bukan hanya individu, tetapi wajah lembaga secara keseluruhan.
Jika tindakan Mikson Yapanto terbukti melewati batas kewenangan, maka mekanisme etik dan kelembagaan harus berjalan. Bukan untuk menghukum individu semata, tetapi untuk menjaga wibawa demokrasi dan marwah institusi yang semakin tergerus oleh perilaku politik transaksional.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak meminta aktualisasi ego seorang anggota DPRD.
Rakyat hanya menuntut satu hal:
“Jalankan tugas sesuai mandat, bukan sesuai selera.”